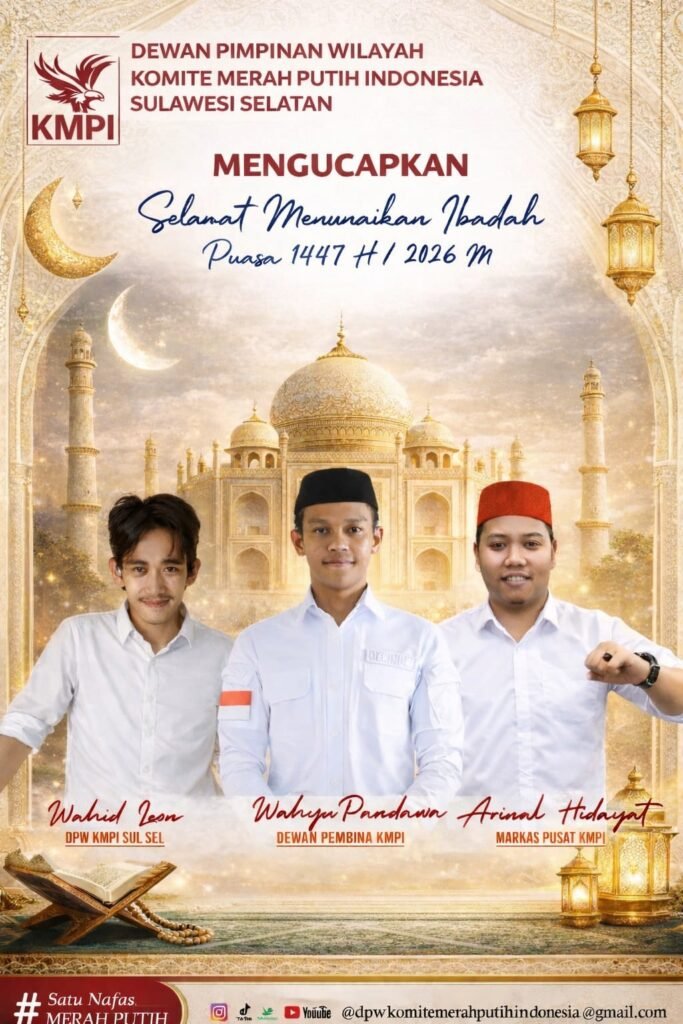DORONGAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mereformasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) demi mendukung aksesi Indonesia ke OECD bukan sekadar agenda teknokratis, melainkan menandai pergeseran besar arah politik hukum nasional. Reformasi hukum kini tidak lagi berdiri murni atas kebutuhan internal pemberantasan korupsi, tetapi mulai bergerak sebagai instrumen legitimasi global agar Indonesia diakui sebagai negara dengan standar tata kelola internasional. (18/2).
Pernyataan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, bahwa reformasi UU Tipikor merupakan “syarat mutlak” menuju keanggotaan OECD memperlihatkan bahwa hukum pidana antikorupsi kini ditempatkan dalam kerangka diplomasi hukum internasional. Aksesi terhadap Konvensi Anti-Suap OECD tidak lagi diposisikan sebagai pilihan kebijakan, tetapi sebagai prasyarat geopolitik yang menentukan posisi Indonesia dalam peta tata kelola global.
Di sisi lain, pengakuan KPK bahwa Indonesia belum mengkriminalisasi secara eksplisit praktik foreign bribery, trading in influence, illicit enrichment, dan bribery in the private sector membuka fakta telanjang adanya kekosongan normatif dalam sistem hukum nasional. Kekosongan ini menjadikan hukum antikorupsi Indonesia timpang: kuat terhadap pelaku birokratik, tetapi lemah menghadapi korupsi korporatis, oligarkik, dan transnasional yang justru menjadi wajah baru kejahatan korupsi modern.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa negara masih tertinggal dalam membaca transformasi korupsi yang telah bergeser dari praktik konvensional ke pola relasi kekuasaan, jejaring bisnis, dan transaksi lintas negara. Tanpa pembaruan substansi hukum, sistem penegakan hanya akan efektif terhadap aktor kecil, sementara aktor besar yang bermain dalam struktur ekonomi-politik global tetap berada di zona aman hukum.
Tekanan aksesi OECD semakin mempertegas posisi Indonesia dalam sorotan internasional. Melalui mekanisme peer review oleh OECD Working Group on Bribery, yang dinilai bukan hanya teks regulasi, tetapi juga keseriusan politik negara dalam membangun sistem antikorupsi yang kredibel dan berkelanjutan. Reformasi hukum tidak lagi cukup simbolik, tetapi harus menyentuh struktur, institusi, dan kultur penegakan hukum.
Namun, di tengah dorongan tersebut, muncul kekhawatiran bahwa revisi UU Tipikor berpotensi terjebak dalam reformasi administratif semata—sekadar memenuhi standar internasional tanpa transformasi substansial. Jika pembaruan hanya bersifat kosmetik regulatif, maka hukum antikorupsi berisiko berubah menjadi etalase global yang rapi di luar, tetapi rapuh di dalam.
Reformasi UU Tipikor kini berada di persimpangan sejarah: apakah akan menjadi fondasi transformasi sistemik pemberantasan korupsi, atau hanya menjadi instrumen politik legitimasi global. Pilihan ini akan menentukan apakah hukum Indonesia benar-benar berdaulat secara moral dan struktural, atau sekadar patuh secara prosedural terhadap standar dunia.