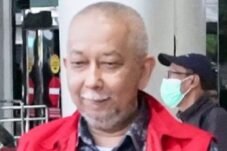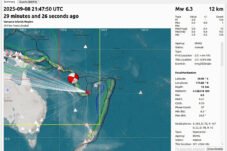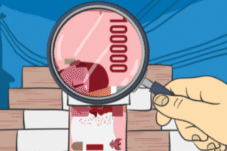Foto & Penulis: Husnul Khatimah (Pengurus Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam HMI Cabang Majene)
INSERTRAKYAT.COM,– Perlindungan anak merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum nasional dan internasional. Namun, prinsip ini seakan kehilangan bentuk ketika seorang ayah—figur utama pelindung anak—malah menjadi pelaku kekerasan seksual. Peristiwa memilukan di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, memperlihatkan hal itu. Seorang ayah berinisial MA (43) diduga memperkosa anak kandungnya berulang kali sejak usia 15 tahun hingga korban melahirkan. Ini adalah potret tragis dari runtuhnya nilai perlindungan anak di ruang domestik. Tindakan pelaku merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 81 ayat (1) dan (3):
- Ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda maksimal Rp5.000.000.000.
- Ayat (3): Jika pelaku adalah orang tua kandung, maka pidana ditambah sepertiga dari ancaman pidana pokok.
Secara hukum, pelaku masuk kategori intrafamilial sexual abuse, yang dikenakan sanksi berat karena terjadi dalam lingkup keluarga dengan relasi kekuasaan yang tidak setara. Kasus ini bukan semata pelanggaran terhadap pasal, tetapi juga bentuk pembangkangan terhadap moralitas hukum dan pelanggaran terhadap non-derogable rights—hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun, termasuk hak anak atas perlindungan dari kekerasan seksual. Pelaku termasuk dalam kategori sexual predator within kinship structure, yakni pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga yang memanfaatkan otoritas dan minimnya kontrol sosial.
Lebih memprihatinkan, fenomena ini bukan kali pertama terjadi di Majene. Pada 2021, publik Majene juga diguncang oleh kasus serupa. Kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga menandakan lemahnya sistem deteksi dini, minimnya edukasi hukum, serta kurangnya keberanian masyarakat untuk melapor. Akibatnya, kasus serupa terus berulang, seolah menjadi pola yang dibiarkan tumbuh dalam diam. Dalam konteks ini, hukum kehilangan peran preventifnya dan baru bergerak setelah korban mengalami kerusakan fisik dan psikis, bahkan setelah kelahiran anak sebagai “bukti hidup” kejahatan. Haruskah selalu menunggu rahim anak menjadi bukti sebelum hukum bertindak? Pertanyaan ini seharusnya menggugah nurani para penegak hukum dan pemangku kepentingan.
Respons negara melalui Polres Majene dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memang ada, namun sayangnya lambat, reaktif, dan terkesan kosmetik. Penanganan hukum dilakukan setelah tragedi terjadi, bukan ketika tanda-tanda awal kekerasan muncul.
Sudah saatnya negara tidak hanya hadir di atas reruntuhan penderitaan korban, tetapi membangun sistem perlindungan yang proaktif. Early warning system harus diperkuat melalui kanal pelaporan rahasia yang aman, pelibatan aktif sekolah, Posyandu, RT/RW, dan perangkat desa guna mendeteksi dan mencegah kekerasan sejak dini. Kasus ini harus menjadi peringatan keras bagi negara dan masyarakat. Perlindungan anak tidak cukup diwujudkan dalam pasal-pasal indah, tetapi dalam sistem sosial yang berfungsi, aparat yang sigap, dan budaya masyarakat yang tidak menoleransi kekerasan sekecil apa pun. Kami tidak ingin kasus serupa terus berulang setiap tahunnya.
Catatan penting lainnya adalah lemahnya peran organisasi perempuan di Majene dalam pendampingan, advokasi, dan edukasi masyarakat terkait perlindungan anak dan kekerasan berbasis gender. Meski jaringan advokasi perempuan ada, peran mereka masih jauh dari optimal. Minimnya sosialisasi, terbatasnya akses terhadap layanan, serta kurangnya pelibatan komunitas perempuan dalam pengawasan sosial membuat keberadaan mereka terkesan sebatas formalitas administratif, bukan kekuatan substantif untuk mencegah tragedi serupa.
Perlu diingat, hukum pidana adalah ultimum remedium—jalan terakhir. Namun, bahkan jalan terakhir itu datang terlambat dalam kasus ini. Semua elemen harus hadir lebih awal, tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi yang lebih penting: menyelamatkan korban sebelum semuanya berubah menjadi luka yang permanen.
Jika rumah tak lagi menjadi tempat aman, dan negara tetap tak peka, kepada siapa lagi anak-anak akan berlindung?. Tabe!. (Red/Isma).
- aparat penegak hukum lamban
- budaya diam masyarakat
- hukum perlindungan anak
- intrafamilial sexual abuse
- kasus perkosaan anak
- kegagalan negara melindungi anak
- kejahatan seksual ayah kandung
- kekerasan berbasis gender
- kekerasan domestik
- kekerasan seksual dalam keluarga
- kontrol sosial lemah
- Majene Sulawesi Barat
- Opini
- pelanggaran HAM anak
- peran organisasi perempuan
- perlindungan anak
- perlindungan perempuan dan anak
- predator seksual
- Sistem Hukum Indonesia
- trauma korban kekerasan seksual
- UU Nomor 35 Tahun 2014