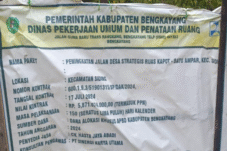JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM, — Refleksi dari rumah pengasingan Sam Ratulangi menjadi renungan bagi setiap punggawa Mahkamah Agung. Di manapun ditempatkan, seorang hakim harus siap melayani, menegakkan keadilan, dan membawa harapan bagi masyarakat.
“Sitou timou tumou tou – manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain”
Semboyan itu lahir dari seorang pahlawan nasional, Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi, atau yang akrab dikenal Sam Ratulangi. Sosok yang lahir di Tondano, Sulawesi Utara, 5 November 1890 ini, dikenang sebagai pejuang kemerdekaan yang mengabdikan diri lewat pendidikan, politik, dan tulisan.
Lingkungan pegunungan, danau, dan budaya Minahasa membentuk Sam kecil sebagai pribadi tekun, terbuka, dan penuh empati. Ia menempuh pendidikan di sekolah Belanda, lalu melanjutkan ke STOVIA di Jawa. Perjalanan intelektualnya berlanjut hingga ke Eropa, di mana ia aktif dalam organisasi mahasiswa dan mulai menanamkan semangat persatuan serta nasionalisme.
Sekembalinya ke tanah air, ia dikenal sebagai guru, penulis, sekaligus tokoh politik. Gagasannya selalu sederhana namun dalam, terutama semboyan yang kini abadi: “Si tou timou tumou tou”.
Pada 5 April 1946, Sam Ratulangi—saat itu menjabat Gubernur Sulawesi—ditangkap Belanda karena menentang dominasi NICA. Setelah dipenjara di Makassar, ia diasingkan ke Serui, Kepulauan Yapen, pada 18 Juni 1946.
Pengasingan yang dimaksudkan untuk membungkamnya justru menjadi ladang pengabdian baru. Hidupnya sederhana: bangun pagi, menyapu halaman, menerima warga dan anak-anak yang datang membawa buku lusuh. Ia mengajar membaca, berhitung, dan bercerita tentang dunia di luar pulau.
Di beranda rumah kayu sederhana, ia menanamkan nilai kejujuran, kerja keras, dan percaya diri. Tak ada papan tulis besar atau seragam sekolah—hanya semangat belajar yang menyatukan guru dan murid.
Rumah pengasingan Sam Ratulangi masih menyimpan jejak kesederhanaannya: cat yang memudar, lantai kayu yang berderit, dan aroma laut Teluk Cenderawasih. Namun dari kesunyian itu, lahir cahaya teladan.
Sam tidak berhenti menulis tentang kemerdekaan dan berbicara tentang kehidupan yang bermartabat. Rumah itu menjadi pusat kecil gagasan besar—bukti bahwa kepemimpinan sejati tak mengenal jarak, jabatan, atau keadaan.
Bagi seorang hakim yang bertugas di Serui, rumah ini bukan sekadar sejarah, tetapi pengingat. Penempatan di ujung timur bukan berarti di pinggir panggung. Justru di sinilah keadilan diuji dalam bentuk paling murni.
Seperti pena Ratulangi yang menulis kata harapan, palu hakim pun harus mengetuk dengan keberanian dan kebijaksanaan. Putusan yang lahir dari meja hijau harus memancarkan integritas, menghormati martabat manusia, dan membangun kepercayaan masyarakat.
Serui mengajarkan bahwa pengabdian sejati tidak diukur dari megahnya ruang kerja atau ramainya tepuk tangan. Ia diukur dari jejak kebaikan yang ditinggalkan.
Hari-hari pengasingan Ratulangi membuktikan bahwa kepemimpinan sejati lahir dalam keterbatasan. Nilai-nilai pendidikan, kerendahan hati, keberanian, inspirasi, dan kemanusiaan tetap relevan hingga kini, terutama bagi hakim yang harus teguh menjaga martabat hukum di manapun ditempatkan.
Serui pun bukan lagi sekadar ujung peta. Ia adalah pusat keadilan dan kemanusiaan.
Berkontribusi dalam artikel ini adalah Bintoro Wisnu Prasojo.