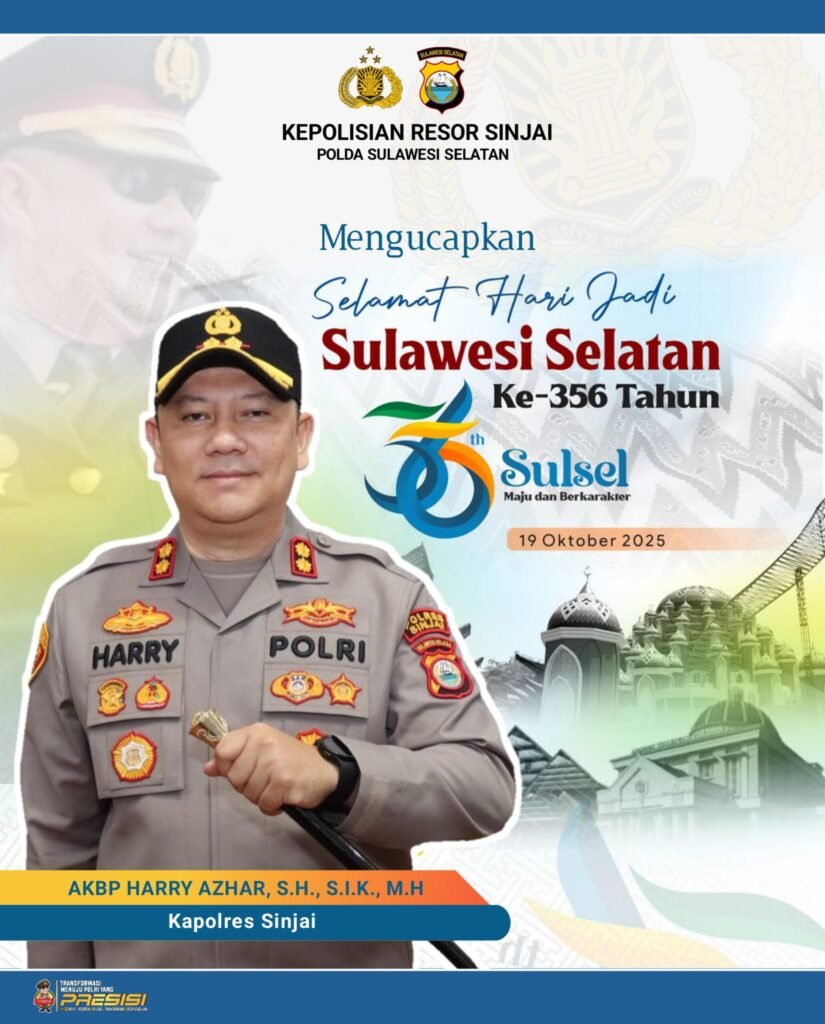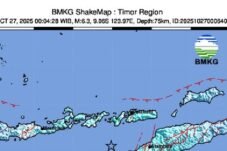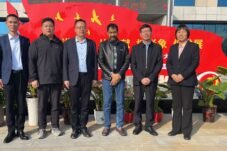JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM,– Krisis sosial kerap merobek sendi kehidupan berbangsa. Jalanan dipenuhi suara protes, air mata keluarga korban jatuh, dan institusi negara dipaksa mempertahankan legitimasinya. Namun dalam pada itu, ada satu kebutuhan [Manusia] tak boleh hilang ialah “keadilan.”
Tanpa keadilan, darurat hanya melahirkan kekerasan yang dilegalkan. Realitas itu kembali terlihat dalam demonstrasi Agustus 2025. Protes yang bermula dari penolakan kebijakan kontroversial berakhir tragis. Affan Kurniawan, pengemudi ojek online, tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Di Makassar, sedikitnya tiga korban jiwa terdiri atas petugas dan warga sipil.
Peristiwa itu mengingatkan pada pola berulang. Dari kerusuhan Mei 1998, konflik Aceh, dinamika Papua, hingga demonstrasi kontemporer, benang merahnya sama: dilema antara stabilitas negara dan hak asasi manusia.
Pengadilan tidak boleh berhenti beroperasi. Justru pada masa krisis, pengadilan diuji: apakah masih mampu menghadirkan rasa keadilan, atau tenggelam dalam logika darurat yang serba represif.
Plato dalam Republic menggambarkan keadilan sebagai harmoni. John Rawls melalui justice as fairness menekankan prinsip kesetaraan yang berlaku universal. Pancasila meneguhkan keadilan sosial sebagai cita-cita bangsa.
Dari perspektif manapun, keadilan tidak boleh absen. Prinsip salus populi suprema lex esto (keselamatan rakyat hukum tertinggi) tidak dapat diartikan sebagai pembenaran mengorbankan hak dasar tanpa prosedur adil dan proporsional.
Hakim dalam situasi darurat menghadapi tekanan ganda. Namun, Aparatur negara mendorong putusan cepat demi efek jera. Argumen yang muncul: keadaan luar biasa membutuhkan langkah luar biasa (exceptio facit legem).
Namun, hak-hak dasar terancam dikorbankan: asas praduga tak bersalah, hak atas bantuan hukum, hingga proporsionalitas hukuman. Tanpa pedoman jelas, hakim bisa terjebak pada dua ekstrem: tunduk sepenuhnya pada logika darurat, atau dianggap tidak responsif terhadap krisis.
Pengalaman internasional menunjukkan perlunya pedoman khusus. Amerika Serikat pasca-9/11 membentuk Emergency Court Administration guidelines. Jerman dengan konsep Wehrverfassung menjaga prinsip negara hukum saat darurat. Inggris melalui Civil Contingencies Act 2004 memberi kerangka pengoperasian hukum dalam krisis.
Indonesia juga punya pengalaman panjang: darurat militer Aceh, status keadaan bahaya di beberapa daerah, hingga darurat kesehatan COVID-19. Namun belum ada standar yudisial yang konsisten.
Pedoman diperlukan bukan untuk membatasi independensi hakim, tetapi menjaga agar setiap putusan tetap berpijak pada keadilan. Standardisasi pendekatan yudisial akan menjamin konsistensi dan akuntabilitas di tengah gejolak.
Pedoman mengadili dalam situasi darurat setidaknya memuat enam hal:
- Kriteria objektif: identifikasi jelas keadaan darurat, gangguan luas, dan ancaman signifikan.
- Prinsip proporsionalitas: pembatasan hak sebanding ancaman, dengan pembedaan provokator dan peserta pasif.
- Proses cepat dan adil: pemeriksaan pendahuluan maksimal 1×24 jam, hak bantuan hukum sejak awal, akses keluarga.
- Standar pembuktian ketat: verifikasi bukti digital, larangan pengakuan di bawah tekanan.
- Perlindungan kelompok rentan: diversi wajib bagi anak, asesmen kesehatan mental, perlindungan jurnalis.
- Oversight dan review berkala: keterlibatan ombudsman dan Komnas HAM, ditutup dengan sunset clause.
Pedoman ini harus diikuti pelatihan khusus bagi hakim dan aparatur peradilan. Masyarakat sipil perlu dilibatkan sebagai pengawas.
Pada akhirnya, pedoman bukan sekadar aturan prosedural. Ia adalah janji moral negara: bahwa bahkan ketika jalanan penuh asap dan tangis, hukum tetap berpijak pada keadilan. Dengan pedoman itu, pengadilan menjadi benteng martabat manusia, bukan alat legitimasi kekerasan.****
Berkontribusi dalam artikel opini ini adalah Muamar Azmar Mahmud Farig