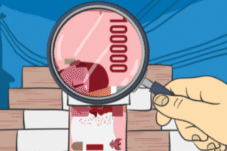Jakarta, Minggu 22 Juni 2025.
Penulis : Guntur Pambudi Wijaya-Ketua PN Kotabaru. (Foto : Guntut). Editor: Supriadi Buraerah Anggota Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung (FORSIMEMA RI).
DALAM tatanan negara hukum, hakim bertindak sebagai pelaksana norma. Hakim adalah penjaga keadilan substantif yang menjunjung tinggi harkat manusia. Paradigma baru hukum pidana nasional kini menempatkan kemanusiaan, etika, dan nilai-nilai sosial sebagai orientasi utama pemidanaan.
Konsepsi ini berpijak pada adagium klasik ubi societas ibi ius: di mana ada masyarakat, di situ hukum hadir.
Dalam hukum modern, hakim tak boleh bersikap proaktif mencari perkara. Tradisi hukum Belanda menyebut hakim sebagai zittende magistratuur, pemegang keadilan yang duduk dan menilai berdasarkan permohonan sah.
Objektivitas menjadi esensi mengikat. Putusan yang sah harus memuat fakta, dasar hukum, dan alasan yuridis sebagaimana diatur Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Pertimbangan yuridis (motivering) menjadi legitimasi utama keputusan hakim.
KUHP Nasional memberi arah baru: pidana bukan lagi alat pembalasan negara. Pemidanaan kini menjadi sarana sosial yang mengedepankan edukasi, koreksi, dan pemulihan keseimbangan masyarakat.
Pandangan ini bukan semata konseptual. Ini berdiri di atas fondasi filosofis yang dalam epistemologis, ontologis, dan aksiologis, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 51 KUHP yang mengatur lima tujuan pemidanaan.
Dalam sudut epistemologis, KUHP baru menolak positivisme hukum yang kaku. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum adalah fenomena sosial yang hidup dan harus dipahami secara manusiawi.
Pasal 51 menampilkan prinsip diversity of sanctions, yakni keberagaman sanksi sebagai bentuk pendekatan hukum yang fleksibel dan kontekstual. Pendekatan ini menolak melihat manusia sebagai objek pasif hukum.
Sudikno Mertokusumo menjawab: hukum adalah kaidah hidup dalam masyarakat. Ia ada bukan di ruang hampa, tetapi tumbuh dari kesadaran kolektif.
KUHP nasional menegaskan bahwa pemidanaan harus bersifat sosial dan proporsional. Pasal 52 hingga 54 memberi hakim keleluasaan mempertimbangkan usia, latar belakang, dan kondisi sosial pelaku.
Kelompok rentan bahkan diberi perlindungan melalui pidana bersyarat di Pasal 65 ayat (1) huruf e. Sementara Pasal 40–44 mengatur alasan pemaaf bagi yang tak layak dimintai tanggung jawab secara moral atau psikologis.
Nilai keadilan menjadi poros utama pemidanaan. Hukum bukan netral. Ia adalah sarana membela martabat manusia.
B. Arief Sidharta menyebut bahwa hakim wajib hidup dalam nilai, bukan sekadar norma. Gustav Radbruch menegaskan, bila keadilan dan kepastian hukum berbenturan, keadilanlah yang harus menang.
KUHP baru menyisipkan semangat itu: menempatkan manusia sebagai subjek, bukan objek. Pemidanaan menjadi sarana pembinaan dan rekonsiliasi, bukan alat pembalasan.
Pasal 54 menyatakan pidana harus menjunjung martabat manusia. Pelaksanaannya diatur rinci dalam Pasal 70–72, dengan mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi bila terjadi pelanggaran.
Hakim, dalam paradigma ini, memegang tanggung jawab etis. Ia bukan sekadar teknisi hukum, tetapi agen pembawa nilai.
Menurut Satjipto Rahardjo, hakim adalah jembatan antara hukum dan realitas sosial. Ia harus berani berpihak pada kemanusiaan. Bukan berarti meninggalkan hukum, tapi menegakkannya dengan rasa keadilan.
KUHP Nasional mendorong peran ini melalui ketentuan pidana yang edukatif, rehabilitatif, dan korektif. Hakim diberi ruang mempertimbangkan nilai, empati, dan konteks sosial dalam putusannya.
Paradigma pemidanaan kini bergerak dari represif ke korektif. Dari prosedural ke substantif. Dari balas dendam ke pemulihan.
Hukum hadir bukan untuk menghukum, tetapi memperbaiki. Hakim adalah penjaga nurani hukum yang harus menyeimbangkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.
Tengok ke dalam kerangka itu, pemidanaan menjadi tugas etis yang tak hanya menilai masa lalu, tetapi memberi harapan bagi masa depan. Sebuah hukum yang memanusiakan, itulah harapan baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hakim aktor Etis dan penjaga kemanusiaan.