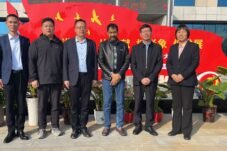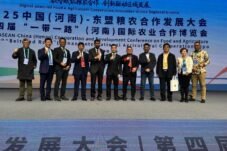LAUT itu biru, tapi birunya bukan warna, melainkan cermin dari langit yang tak punya bentuk. Di atas laut yang luas, sembilan kapal berlayar dari sembilan penjuru, masing-masing membawa satu raja dengan mahkota berkarat dan dada penuh sesak karena terpapar “masuk angin”. Kedoknya, mereka bukan raja yang mencari tanah jajahan, melainkan raja yang mencari arti dari “berita cinta” yang dikabarkan berembus dari arah timur. Konon, siapa pun yang mengerti makna cinta itu akan menemukan keseimbangan antara memberi dan menimbun, antara mengambil dan melepaskan.
Namun laut punya hukum sendiri. Ia tak mengenal rem. Kapal bisa berhenti, tapi bukan karena keinginan manusia. Kapal hanya bisa berhenti bila laut mengizinkan, bila angin menunduk, bila ombak sepakat melunakkan dirinya. Maka ketika kesembilan raja berlayar, mereka tak tahu bahwa perjalanan mereka bukan tentang arah, tapi tentang makna di balik tiupan angin yang mereka sangka kabar cinta.
Abunawas muncul di tengah samudra, bukan sebagai penguasa, tapi sebagai penonton yang bijak dan jenaka. Ia berdiri di atas perahu kecil yang diikat dengan tali dari bayangan matahari. “Kapal-kapal itu,” katanya pada laut, “tak punya rem, tapi bisa berhenti bila kesombongan mereka karam.” Laut diam, tapi setiap percikan air menjadi jawaban.
Raja pertama datang dari utara, membawa emas dalam peti besar. Ia berkata, “Angin harus bisa kubeli.” Ia memerintahkan pelautnya meniup layar dengan napas sendiri. Kapalnya melaju, tapi hanya sebentar. Emas di peti berubah beban, dan kapal tenggelam perlahan. Dari jauh, Abunawas tersenyum getir, menulis di udara: ketika kekayaan terlalu berat, bahkan angin pun enggan bersahabat.
Raja kedua datang dari selatan. Ia tak membawa emas, tapi membawa suara—seribu kabar dari istana yang jauh. Ia berteriak di atas laut, menanyakan arah berita cinta yang katanya berembus dari timur. Namun suaranya hanya memantul di antara gelombang. Ia mendengar gaungnya sendiri, lalu mengira itu jawaban. “Cinta telah menjawabku!” serunya. Tapi laut tahu, yang ia dengar hanyalah egonya sendiri. Abunawas menulis lagi di udara: manusia sering salah paham; gema dianggap wahyu, padahal hanya pantulan dirinya.
Raja ketiga dari barat membawa armada penuh prajurit. Ia yakin cinta adalah kemenangan. Di atas kapal besi, ia mengatur formasi barisan, menyiapkan meriam yang tak tahu musuh. Ketika angin datang terlalu kencang, kapal-kapalnya saling bertabrakan. Tak ada perang, tapi kehancuran tetap datang. Abunawas kembali menulis: kekuasaan yang tak tahu arah, akan memerangi dirinya sendiri.
Raja keempat dari timur membawa cermin besar. Ia ingin melihat wajah cinta yang dikabarkan itu. Tapi di tengah laut, cermin hanya memantulkan langit dan ombak. Ia marah, ia kira laut menipunya. Dalam amarahnya, ia melempar cermin ke laut. Air tertawa dalam riak, memantulkan wajahnya sendiri dari permukaan. “Itulah dirimu, wahai raja,” kata Abunawas dari kejauhan. “Engkau ingin melihat cinta, tapi yang kau cari hanya pantulan.”
Empat raja karam oleh kesalahpahaman, lima lainnya datang berikutnya dengan langkah yang lebih misterius. Raja kelima datang membawa satu mobil laut—kendaraan yang tak seharusnya ada. Di atasnya, 40 butir telur tersusun di peti kayu. Ia berkata, “Cinta adalah keseimbangan, seperti 40 telur di atas mobil laut ini. Tak boleh satu pun jatuh.” Namun ketika ombak datang sedikit tinggi, satu telur terguling, pecah, dan dari dalamnya keluar burung laut kecil. Ia terbang ke langit. Raja itu menangis, bukan karena kehilangan telur, tapi karena ia sadar: keseimbangan sejati bukan menjaga agar tak ada yang berubah, tapi menerima bahwa sesuatu harus pecah agar kehidupan baru lahir. Abunawas mengangguk: itulah hikmah dari retakan: pecah untuk menyempurna.
Raja keenam datang membawa buku besar berisi hukum. Ia berkata, “Angin harus diatur. Cinta harus ditulis dalam pasal.” Ia menulis aturan arah tiupan, tetapi angin justru menertawakannya. Lembaran hukum itu terbang satu per satu, jatuh ke laut, menjadi sarang ikan-ikan kecil. “Lihatlah,” kata Abunawas, “kata-katamu menjadi makanan, bukan pedoman.” Laut menyimpan diam, tapi diamnya adalah tawa panjang.
Raja ketujuh datang dengan kapal dari batu. Ia ingin membuktikan bahwa keteguhan bisa mengalahkan gelombang. Tapi kapal batu itu berat dan tenggelam sebelum sempat berlayar jauh. Dari dasar laut, gema suaranya naik: “Aku tak bergerak, tapi aku kokoh!” Abunawas menulis di udara: batu yang tak bergerak bukan simbol kekuatan, tapi tanda ketakutan pada perubahan.
Raja kedelapan datang membawa cangkir kosong. “Aku tak punya apa-apa,” katanya. “Tapi mungkin cinta bisa mengisinya.” Ia memungut air laut dan meneguknya. Asin. Ia tertawa. “Ternyata cinta punya rasa asin.” Abunawas menatapnya lama. “Kau tak salah,” katanya. “Cinta memang asin, karena ia adalah air mata dunia. Tapi justru karena itu, ia membuat kita hidup.” Laut bergetar, seperti berdoa.
Raja kesembilan datang terakhir, tak membawa apa-apa. Kapalnya hanya selembar papan yang ditambatkan pada bayangan angin. Ia tidak bertanya, tidak memerintah, tidak menuntut. Ia hanya mendengarkan bunyi laut, menghitung waktu lewat ritme ombak. Ketika angin berhembus lembut, kapalnya berhenti perlahan tanpa rem. Laut menenangkan dirinya di sekelilingnya. Abunawas berbisik: itulah jawaban dari semua perjalanan. Cinta adalah kemampuan berhenti di tengah gerak tanpa merasa kalah.
Kesembilan raja itu akhirnya berkumpul di satu pulau yang tak ada di peta. Di sanalah Abunawas berbicara di hadapan mereka:
“Wahai para penguasa, kalian datang dari sembilan arah dengan beban berbeda, tapi mencari hal yang sama. Kalian menyangka cinta adalah berita yang datang dari luar, padahal ia adalah tiupan yang sejak awal bersemayam di dada kalian sendiri. Kalian menimbun angin dalam peti, menakar cinta dengan emas, menulisnya dengan hukum, menegakkannya dengan batu. Tapi cinta tak mengenal timbunan. Ia hanya mengalir.”
Salah satu raja bertanya, “Apakah cinta itu tidak bisa disimpan?”
Abunawas tersenyum. “Cinta yang disimpan membusuk. Sama seperti telur yang tak menetas. Cinta hanya bisa tumbuh bila dibiarkan pecah, seperti 40 telur di atas mobil laut itu. Ada yang retak, tapi dari retakanlah burung laut belajar terbang.”
Mereka terdiam. Angin berembus pelan, membawa harum garam dan sunyi. Dalam kesunyian itu, laut tampak seperti cermin besar yang memantulkan bukan wajah mereka, tapi bayangan hati manusia: serakah, takut, ragu, tapi juga penuh harapan.
Raja dari utara menunduk, mengeluarkan emas dari sakunya, lalu melemparnya ke laut. Raja dari selatan berhenti berteriak. Raja dari barat menurunkan meriamnya. Raja dari timur mengambil kembali cermin yang terapung. Raja kelima memecahkan sisa telur di tangannya dan membiarkan isinya mengalir ke air. Raja keenam menutup bukunya. Raja ketujuh membiarkan kapalnya tenggelam sepenuhnya. Raja kedelapan menenggak air laut lagi dan tersenyum. Raja kesembilan tetap diam, matanya menatap ufuk.
Abunawas tahu, pelajaran itu bukan untuk mereka semata, melainkan untuk siapa pun yang hidup di daratan yang terus menimbun—entah harta, entah jabatan, entah kebenaran. Dunia modern, pikir Abunawas, tak jauh beda dari sembilan raja itu. Orang-orang terus menimbun sesuatu yang tak pernah cukup, menamai keserakahan sebagai kerja keras, menamai penimbunan sebagai investasi, menamai diamnya hati sebagai kedewasaan.
Laut tetap biru, tapi biru itu kini tampak lebih dalam. Angin membawa sisa kata-kata Abunawas ke segala arah:
“Berita cinta bukanlah kabar yang ditulis oleh kuli tinta di istana, melainkan pesan yang ditulis oleh hidup itu sendiri. Setiap kali engkau menimbun, engkau kehilangan ruang untuk angin lewat. Dan tanpa angin, kapalmu akan berhenti bukan karena rem, tapi karena mati.”
Langit memudar di cakrawala, membentuk bayangan kapal yang tak berlayar namun juga tak karam. Abunawas duduk di perahunya yang kecil, menatap sembilan raja yang kini belajar menunduk. Di tangannya, ia memegang pena dari bulu camar dan menulis di udara satu kalimat terakhir:
“Manusia mencari cinta di tempat angin berhembus, padahal ia bersemayam di ruang kosong antara satu napas dan napas berikutnya.”
Gelombang terakhir menyentuh kaki perahunya. Dalam dunia senyatanya, kapal laut seakan berhenti sejenak—tanpa rem, tanpa perintah. Hanya berhenti. Karena mungkin untuk pertama kalinya, dunia sedang benar-benar mendengarkan kilas balik jelang periode terdengar desas – desusnya, 500 Juta Suara Emas menggema ke dalam sunyi yang tertutup cangkang 40 butir telur. Bilakah kebenaran terungkap, dan moga tidak dengan Oke Tuan – Tuan (OTT) Kilas Pedas (KPK) bedah makna. (Ag).